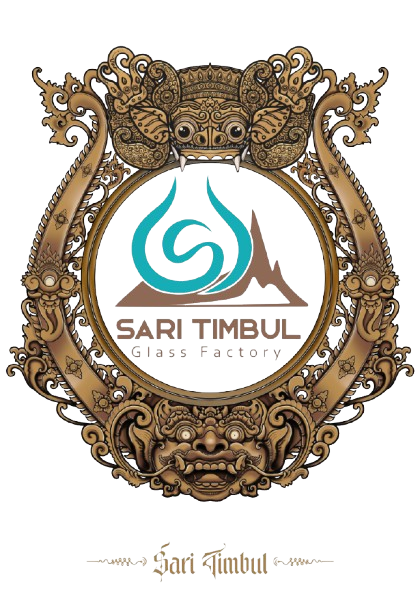Tantri
Berkisah tentang Raja Aeswaryadala yang rakus seksualitas. Kisah awal ini dapat disandingkan dengan kisah-kisah mengenai raja-raja kuno yang beristri banyak salah satu penciri kekuasaan adalah memiliki banyak istri atau selir. Masalah dimulai ketika hanya tersisa satu orang gadis bernama Ni Dyah Tantri, yaitu anak perempuan satu-satunya dari Patih Bandeswara, orang kepercayaan yang ditugaskan untuk selalu menyediakan seorang gadis setiap malam. Bukannya menolak, Tantri justru dengan berani mengajukan dirinya sebagai solusi kegalauan ayahnya. Singkat cerita, Tantri pun berakhir di peraduan Aeswaryadala. Akan tetapi, tidak seperti gadis- gadis sebelumnya yang pasrah dengan tubuhnya, Tantri justru bercerita, mendongeng tentang kehidupan di hutan belantara.
Latar awal istana dalam cerita Ni Dyah Tantri dilebur menjadi hutan belantara; erotisme diruwat menjadi kisah binatang. Bagaimana menghubungkan istana dengan hutan belantara? Bagaimana seorang raja yang absolut disejajarkan dengan binatang? Inilah perpaduan politik (niti) dengan sastra, politik sastra. Ni Dyah Tantri telah berhasil mengganti tubuhnya dengan sastra; ia mengganti setiap organ tubuhnya dengan aksara. Kegadisan Tantri menjadi teks, begitu pun nafsu seksual raja dikonversi menjadi emosi imajinatif.
Pada akhirnya, Ni Dyah Tantri meninabobokkan anak kecil bernama hasrat seksual. Tidak menampik, seksualitas adalah hasrat purba manusia setelah insting bertahan hidup. Tak pelak, para leluhur Hindu lebih memilih untuk memuja hasrat itu dalam bentuk Lingga-Yoni dan menyebutnya dengan Purusha-Predana, daripada mengumbarnya sembarangan. Leluhur Bali mentransmutasikannya secara lebih estetis, menjadi patung-patung raksasa atau kera dengan ‘alat kelamin super besar’, menjadi Calonarang. Belakangan bangunan Padmasana dengan Badawangnala di bawahnya juga diduga terinsipirasi dari Lingga-Yoni.
Kesadaran Raja Aeswaryadala dibalik dengan amuter tutur pinahayu. Nafsu sang raja (rajas) dimetaforakan sebagai binatang (satwa). Dengan begitu, terjadi pembandingan dalam pikiran sang raja, sampai akhirnya terjadi penyamaan dan pengkontrasan eksistensial antara dirinya dengan binatang seperti lembu, singa, serigala, kura-kura, burung, kambing, dlsb. dengan strategi metaforik. Analoginya seperti seorang laki-laki ketika dikatai oleh seorang perempuan, “dasar laki-laki!”, atau seorang anak kecil secara terus menerus dikatai atau dibully dengan menyebutnya “anak kecil!” ada perasaan bimbang antara menolak dan menyetujui secara simultan.
Ada kebimbangan eksistensial. Kebenaran absolut sang raja yang dilampiaskan dengan seksualitas perlahan digoyahkan sampai akhirnya menyetujui. Ia mengalami historisitas cerita-cerita yang disuguhkan Tantri. Ni Dyah Tantri telah mengetuk kesadaran Raja Aeswaryadala. Sama halnya dengan ketika Sri Krsna mengajarkan Samkhya kepada Arjuna di medan Kurusetra, seperti Siwa juga mengajarkannya kepada Parwati dalam Siwa Purana. Tantri membangkitkan kecerdasan diskriminatif (wiweka) Aeswaryadala. Sehingga, hasrat seksual bergelora disublimasi menjadi emosi lalu menyembul menjadi cinta kasih.
Di akhir kisah, Tantri disunting menjadi permaisuri Raja Aeswaryadala. Ia telah membongkar aksioma sang raja mengenai perempuan, dari ‘pemuas nafsu’, ‘tak berdaya; lemah’, atau ‘objek seksualitas’ menjadi ‘ratu’, ‘pujaan’, ‘kekasih; sakti ‘kekuatan’, ataupun ‘subjek seksualitas’. Ia bahkan meleburkan dikotomi subjek-objek menjadi intersubjektivitas, Ardanareswari. Strategi politik Ni Dyah Tantri adalah prayascita. Inilah politik sastra (teks), politik tantra, politik tubuh, yang sedikit berbeda dengan ‘politik tubuh’ menurut Foucault. Tantri mengubah jiwa totaliter Aeswaryadala menjadi demokrasi. Kekotoran telah disucikan dengan sastra.